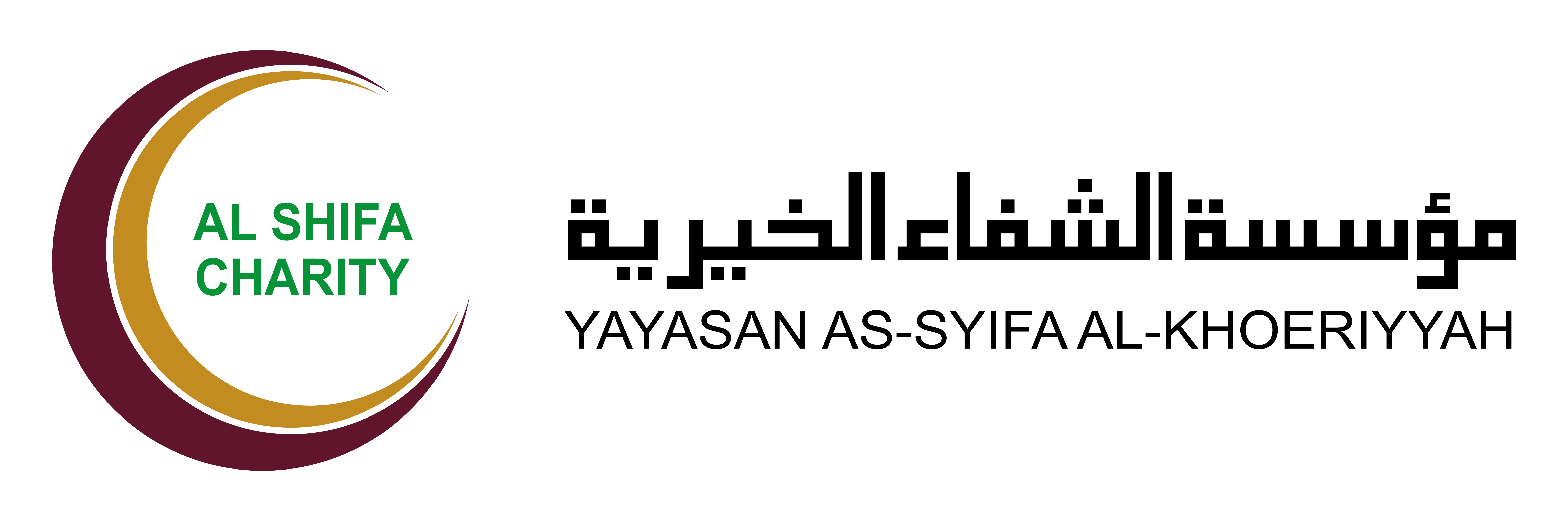Saya Cuma Murid Percobaan
Akhir-akhir ini, linimasa dibeberapa sosial media diisi oleh protes beberapa orangtua dan sebagian murid yang memprotes sistem zonasi sekolah negeri yang ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Hal ini menutup kemungkinan calon murid untuk masuk ke sekolah unggulan negeri. Karena peraturan ini berdasarkan jarak sekolah dengan tempat tinggal.
Jadi ingat waktu masih SMP dulu. Tiap hari naik angkot berjarak hampir 10 kilometer tiap hari untuk bisa ke sekolah. Walaupun saya di sekolah Islam swasta, tapi SMP negeri unggulan kebetulan dekat dengan SMP saya. Dan kawan-kawan SD saya dulu banyak juga yang sekolah di SMP unggulan itu yang jarak rumahnya bahkan lebih jauh.
Ok, itu SMP. Saat hendak masuk SMA, waktu itu lagi boomingnya novel Negeri 5 Menara. Sebuah novel yang menceritakan kehidupan seorang santri di pesantren Gontor Ponorogo nun jauh dari kampungnya di Maninjau Sumatera Barat. Gimana nggak tertarik, pas saya SMP kebetulan saya, dan kawan-kawan serta guru-guru saya mengundang penulis novel ini ke sekolah dalam acara talkshow milad sekolah. Apalagi novel ini dijadikan film layar lebar. Makin besar tekad saya buat jauh-jauh pergi dari rumah. Haha…
Kalau di novel, orang tuanya yang memaksa Alif untuk mondok di Gontor, saya kebalikannya. Saya yang minta nyantri di Jawa. Akhirnya saya mulai cari brosur-brosur pesantren terpadu. Mulai yang di Anyer, Bogor, Kuningan, Lembang dan Subang. Saya pilih yang di Subang. Bukan apa-apa, biayanya lebih murah dan masuknya lebih mudah dulunya. Karena orientasi saya harus nyantri dan jauh dari rumah.
Singkat cerita, saya lulus dan mulai masuk ke pesantren di pedalaman Subang ini. Anak-anaknya memang dari penjuru. Tapi tampaknya kami bukan murid-murid pilihan. Yang daftar pun juga sesuai kuota. Kasarnya mah, kalo daftar dijamin lulus juga. Dan satu lagi yang saya lupa perhatikan. Saya adalah murid angkatan 2. Jadi ini pesantren masih baru. Gedungnya juga baru. Bau catnya masih ingat saya, Catylax mereknya. Hehe…, Jadi, ini pesantren baru. Akreditasi waktu itu belum ada. Guru-gurunya muda-muda. “Kira-kira apakah saya bisa kayak Alif di novel itu ya?” Batin saya.
Kehidupan pesantren saya jalani. Saya masih dengan ekspektasi yang tinggi dari pesantren ini. Tapi saya harus sadar, ini pesantren baru yang belum punya jejak apalagi alumni. Maka di akhir semester 1 saya gamang dan bilang ke ibu saya untuk pindah dari Subang. Saya takut nggak bisa kuliah di PTN, nggak bisa jadi apa-apa.
Saat kembali, saya sampaikan itikad saya pada guru di pesantren. Mereka tampak kaget dengan keputusan saya. Dan ibu saya malah sudah konsultasi lebih dulu ke guru BK. Intinya supaya saya bisa bertahan di Subang. Dan itu pinta ibu saya. Walau ibu saya guru sekolah negeri, tapi sangat peka soal pendidikan agama. Dan saya tersentak dengan nasihat ustadz besar di pesantren, bahwa di mana pun kita berada, maka di situlah kita semestinya berjuang. Kalau belum baik lingkungan kita, harusnya kita jadi pelopor kebaikan di sana juga. Jleb. Saya terlalu banyak menuntut dan terlalu tinggi dengan ekspektasi. Sulit sekali menerima realita.
Allah menempatkan kita bukan di mana kita inginkan. Tapi di mana kita dibutuhkan.